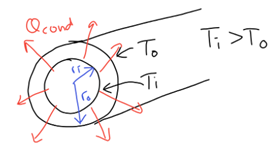Pada saat merancang sebuah mesin pendingin peltier, maka salah satu tahapnya adalah menentukan berapa banyak modul peltier yang dibutuhkan. Untuk hal ini perlu dilakukan perhitungan agar tidak membuang waktu dan biaya. Contoh yang biasa ditanyakan adalah misal:
- Untuk
mendinginkan sebuah box berukuran 20 x 40 x 50 cm, berapa modul peltier
(termoelektrik) yang dibutuhkan?
- Untuk
ruangan 2 m x 3 m, apakah bisa pakai pendingin termoelektrik? Jika bisa,
berapa modul peltier yang dibutuhkan?
Sebenarnya untuk menjawab pertanyaan seperti
ini tidaklah semudah itu, kenapa?
Karena informasinya tidak lengkap. Contoh
untuk kasus nomor 1, kita butuh informasi bahan boxnya terbuat dari apa,
tebalnya berapa? suhu di dalam box dirancang berapa?
Tanpa informasi
yang lengkap maka akan sulit menentukannya dan yang bisa dilakukan hanyalah
dengan metode trial and error. Metode
ini dilakukan dengan cara mencoba lalu jika tidak berhasil maka dicoba lagi
dengan cara berbeda, jika belum berhasil, dicoba lagi dan seterusnya.
Akibatnya, cara ini butuh waktu dan biaya yang cukup besar.
Metode yang lebih baik adalah dengan cara diperhitungkan dari awal dengan informasi yang ada atau asumsi yang bisa diterapkan. Namun, metode ini membutuhkan pemahaman yang cukup setidaknya di bidang perpindahan kalor dan prinsip termoelektrik. Secara umum metode ini terdiri beberapa langkah yang dapat digambarkan dalam gambar berikut:
Tahapan proses perancangan sistem pendingin termoelektrik yaitu:
- Permasalahan atau problem yang ingin diselesaikan harus jelas
batasan-batasannya.
- Dari informasi permasalahan yang ada, dapat dilakukan perhitungan
beban pendinginannya, yaitu laju kalor yang harus dilepaskan dari objek
yang ingin didinginkan.
- Setelah nilai beban pendinginannya didapat, selanjutnya perlu
dilakukan kapasitas pendingin untuk satu modul peltier yang digunakan.
Tentu saja disesuaikan dengan masalah yang akan dipecahkan.
- Selanjunya dapat menghitung berapa modul termoelekrtrik (peltier)
yang dibutuhkan
- Lalu, diperlukan komponen-komponen pendukungnya: heat sink, power supply, thermal interface material, dan lainnya. Lalu semua komponen ini dikonstruksikan agar dapat bekerja untuk memecahkan masalah
- Setelah itu, sistem pendingin yang sudah dibuat perlu diujikan. Jika masih belum bisa sesuai dengan yang dirancang maka perlu dimodifikais kembali.
Untuk informasi
pendaftaran workshop, dapat dilihat di:
https://www.instagram.com/raymtech.official?igsh=NXZwam1jNTB3ZHdo
https://bit.ly/Raymtech_TEworkshop
Untuk mempelajari tentang
termoelektrik:
https://catatan-teknik.blogspot.com/p/thermoelectric_3.html
(Tri Ayodha Ajiwiguna)
Keyword: Thermoelectric, Peltier, Termoelektrik, sistem pendingin, refrigerasi